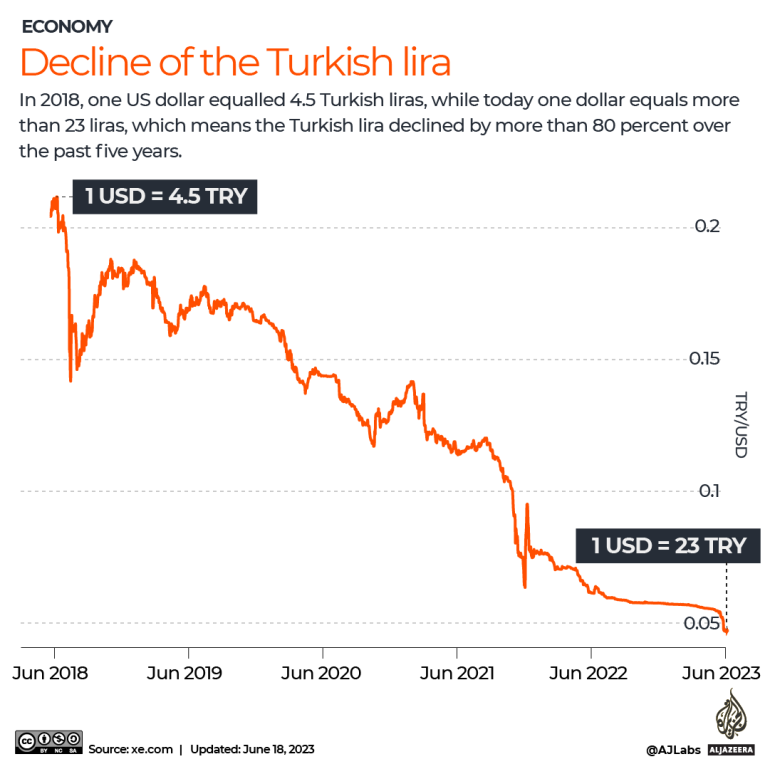Cisarua, Indonesia – Sejak kembali berkuasa di Afghanistan, Taliban telah mencoba membungkam perempuan, tetapi ribuan kilometer jauhnya di Indonesia – di mana banyak yang melarikan diri untuk menghindari penganiayaan – perempuan Afghanistan menemukan suara mereka.
“Di sini perempuan bisa menjadi bos; mereka bisa menjadi guru, mereka bisa menjadi siswa… mereka kuat,” kata Khatera Amiri yang berusia 26 tahun kepada Al Jazeera.
Khatera adalah manajer dari Pusat Pembelajaran Pengungsi Cisarua (CRLC)yang pada tahun 2014 merupakan pusat belajar pengungsi pertama yang didirikan di Cisarua, Kabupaten Bogor, 80 km (50 mil) selatan Jakarta.
Didirikan oleh sekelompok pengungsi Hazara, para pendiri awalnya beralih ke pria yang bekerja sebagai guru di Afghanistan untuk memimpin kelas, tetapi setelah mereka menolak, karena takut akan membahayakan klaim perlindungan mereka, para wanita tersebut melangkah maju.
Saat ini setidaknya ada tujuh pusat pembelajaran yang dipimpin pengungsi di Bogor yang melayani sekitar 1.800 anak, serta tiga di Jakarta dan satu di ibu kota Thailand, Bangkok. Mengingat potensi relokasi ke negara ketiga, bahasa Inggris adalah bahasa pengantar.
“Ini transformatif – terutama untuk perempuan muda,” kata Lucy Fiske, akademisi senior di University of Technology Sydney, yang menghabiskan enam tahun meneliti dampak pusat pembelajaran pengungsi terhadap perempuan Hazara.
Fiske tetap berhubungan dengan banyak pengungsi yang dipindahkan ke tempat lain.
“Apa yang kami lihat sekarang adalah orang-orang langsung pergi dari sekolah-sekolah ini ke universitas,” katanya.

Banyak guru di pusat pembelajaran, seperti Khatera, mulai sebagai siswa dan menjadi guru. Tumbuh di Ghazni di Afghanistan tengah, Khatera adalah murid yang berbakat. Dia melewatkan beberapa nilai dan menyelesaikan kursus akuntansi pada usia 19 tahun.
Dia melarikan diri ke Indonesia pada tahun 2016 bersama tiga saudara kandungnya, yang termuda berusia 14 tahun saat itu, setelah Taliban menculik ibu, saudara laki-laki, dan saudara perempuannya yang berusia delapan tahun.
“Saya harus menyelamatkan saudara laki-laki dan perempuan saya,” katanya.
menemukan kedamaian
Seperti kebanyakan pengungsi, Khatera melakukan perjalanan ke India dan Malaysia sebelum tiba di india.
Pada Februari, ada beberapa 12.710 pengungsi terdaftar dengan Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) di negara itu, lebih dari separuh Afghanistan dan sebagian besar orang Hazara. Dikatakan sebagai keturunan Jenghis Khan, suku Hazara adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Afghanistan dan berasal dari dataran tinggi tengah negara itu. Mereka mengatakan telah lama dianiaya, termasuk oleh Taliban.
Banyak yang tiba di Indonesia berharap untuk naik kapal ke Pulau Christmas, sebuah wilayah Australia di lepas pantai selatan pulau Jawa Indonesia, tetapi ketika Australia meluncurkan Operasi Perbatasan Berdaulat pada September 2013 – dan kebijakan imigrasi Pulau Pasifik yang terkenal buruk diterapkan – banyak yang mendapati diri mereka sendiri terjebak.
Cisarua sekarang menjadi rumah bagi sekitar 5.000 orang yang sebagian besar merupakan pengungsi Hazara dan banyak yang telah hidup terlantar selama satu dekade, berharap mendapat kesempatan untuk bermukim kembali.
Angka terbaru dari laporan UNHCR tentang pemindahan paksa menunjukkan bahwa hanya 114.300 orang di seluruh dunia yang diberi kesempatan itu pada tahun 2022.
Ketika Khatera tiba di Indonesia, dia pergi ke Cisarua, tetapi tinggal jauh dari warga Afghanistan lainnya, dia mengatakan bahwa dia mengalami intimidasi dan pelecehan seksual.
“Tahun 2016 dan 2017 merupakan bencana yang penuh tantangan dan kesulitan, dan saya tidak akan pernah melupakannya. Tidak ada yang mendukung saya,” katanya, “Saya orang tua di sini; Saya memiliki tanggung jawab atas tiga saudara kandung, terutama di komunitas yang asing; kamu tidak bisa mempercayai siapa pun.”
Suatu hari Khatera bertemu dengan salah satu guru CRLC ketika dia berada di kota dan dia mendorong dia dan saudara-saudaranya untuk mengikuti kelas di CRLC. Itu adalah tempat pertama yang dia rasa aman sejak melarikan diri dari Afghanistan. Dia belajar bahasa Inggris, matematika, sains dan Bahasa Indonesia, dan kepercayaan dirinya tumbuh.
“Saya menemukan kedamaian di sini, saya menemukan komunitas, saya menemukan versi terbaik dari diri saya,” katanya.

Keterampilan kepemimpinannya diakui dan dia didorong untuk melamar menjadi seorang guru. Dia menjalankan program GED, yang diajarkan secara online oleh para guru di Australia dan memungkinkan siswa untuk mendapatkan yang setara dengan diploma sekolah menengah AS.
Khatera saat ini sedang menyelesaikan GED-nya. Dia berencana untuk mengikuti dua ujian pertama akhir tahun ini.
“Tujuan saya lebih besar. Impian saya lebih besar, saya ingin ijazah saya dari universitas, saya ingin pekerjaan yang bagus sehingga saya bisa berada dalam situasi keuangan yang baik,” katanya kepada Al Jazeera.
Indonesia bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, tetapi mengadopsi undang-undang pengungsinya sendiri pada Desember 2016, yang memberikan akses dan perlindungan sementara kepada pengungsi di negara tersebut hingga solusi jangka panjang dapat ditemukan.
Mereka yang terdaftar di badan pengungsi PBB dapat tinggal di komunitas – meskipun mereka tidak diizinkan bekerja – dan menyekolahkan anak mereka ke sekolah lokal.
Namun, pada kenyataannya, tidak ada undang-undang di Indonesia yang melindungi hak anak-anak pengungsi atas pendidikan dan mereka menghadapi banyak kendala untuk mengakses sekolah lokal, termasuk kendala bahasa dan gangguan pendidikan mereka akibat pengungsian.
Perbedaan yang positif
Di masyarakat, siswa dan guru sering berpindah-pindah pusat belajar pengungsi. Khatera Jamshidzada (27), yang juga dipanggil Sofie, mengajar di dua pusat belajar pengungsi di Cisarua.
“Mengajar adalah hobi saya; ketika saya mengajar, saya melupakan masalah saya.”
Sofie adalah seorang guru di Afghanistan tetapi Taliban mengancamnya dan menyerang sekolahnya.
“Ketika saya meninggalkan Afghanistan, saya pikir saya tidak akan pernah mengajar lagi,” katanya kepada Al Jazeera.
Sejak kembali mengajar di Indonesia, ia juga mengajar anak-anak pengungsi dari negara lain.
“Saya sangat bangga saat mulai mengajar lagi, karena saya masih bisa membantu banyak anak dari berbagai negara dan budaya berbeda, bukan hanya anak Afghanistan.”
Sofie merasa dengan mengajar dia bisa memberikan masa kanak-kanak yang dirindukan oleh anak-anak pengungsi. “Saya bisa menjadi orang yang positif di masa depan mereka.”
Salah satu murid pertama CRLC adalah Farahnaz Salehi, yang kini berusia 24 tahun.
Dia telah berada di Indonesia selama 10 tahun dan mengingat bagaimana dia dan keluarganya mengisolasi diri pada awalnya.

Mereka tidur hampir sepanjang hari dan menyendiri, takut jika mereka bercampur dengan keluarga pengungsi lain, mereka akan dideportasi kembali ke Afghanistan.
“Saya adalah gadis yang sangat pemalu di negara saya sendiri. Saya nakal… tetapi saya tidak memiliki banyak keberanian untuk berbicara dan berbicara dengan suara keras, tetapi hari ini saya bisa, ”katanya.
Farahnaz didorong untuk mengejar kecintaannya pada seni dan juga bermain sepak bola untuk pertama kalinya. Olahraga membantunya mengatasi ketidakpastian kehidupan pengungsi dan sementara ibunya enggan membiarkannya terus bermain, dia akhirnya mengalah.
Kini, setelah mengajar seni di CRLC selama tujuh tahun, Farahnaz fokus pada karyanya sendiri dan berharap bisa menggelar pameran seninya.
“Saya menjadi diri saya karena CRLC,” katanya.
Sementara pusat belajar pengungsi di Bogor menjadi sumber kebanggaan bagi masyarakat, pembatasan kemampuan pengungsi untuk bekerja dan belajar serta ketidakpastian kehidupan pengungsi diperparah oleh pandemi dan kembali berkuasanya Taliban.
Setidaknya 13 pengungsi telah meninggal karena bunuh diri sejak 2014.
Sedikitnya tempat yang tersedia dalam program pemukiman kembali berarti bahwa beberapa pengungsi dapat berada di Indonesia selama 25 tahun sebelum menemukan rumah permanen.
Namun, juru bicara UNHCR Indonesia mengatakan kepada Al Jazeera bahwa, sejak pengambilalihan Taliban, banyak negara pemukiman kembali telah menambah jumlah tempat yang tersedia.
“Kami berharap peningkatan jumlah slot pemukiman kembali dapat membantu lebih banyak pengungsi Afghanistan di negara tersebut menemukan solusi,” kata juru bicara itu.

Meskipun kelelahan selama bertahun-tahun dalam limbo, Khatera, Sofie, dan Farahnaz percaya bahwa perlakuan terhadap wanita di Afghanistan memicu kebutuhan mereka untuk berjuang lebih keras.
“Teman saya yang tinggal di Amerika sekarang, dia mengatakan kepada saya, Farahnaz… Wanita di Afghanistan, mereka tidak memiliki suara untuk berbicara tentang apa yang terjadi dalam hidup mereka – Anda mencoba menjadi suara mereka…” kenang Farahnaz.
“Aku merasakan apa yang dia katakan.”